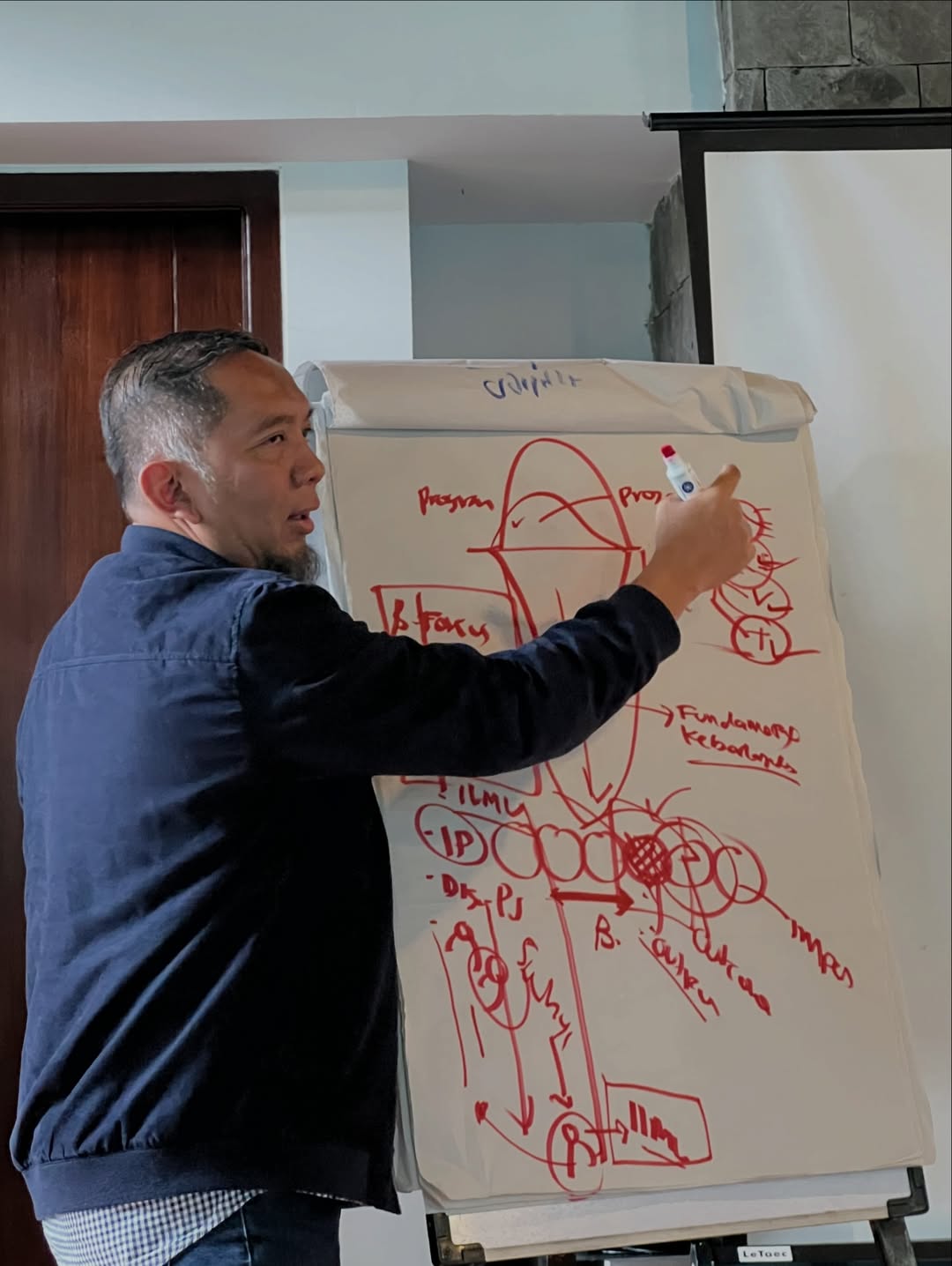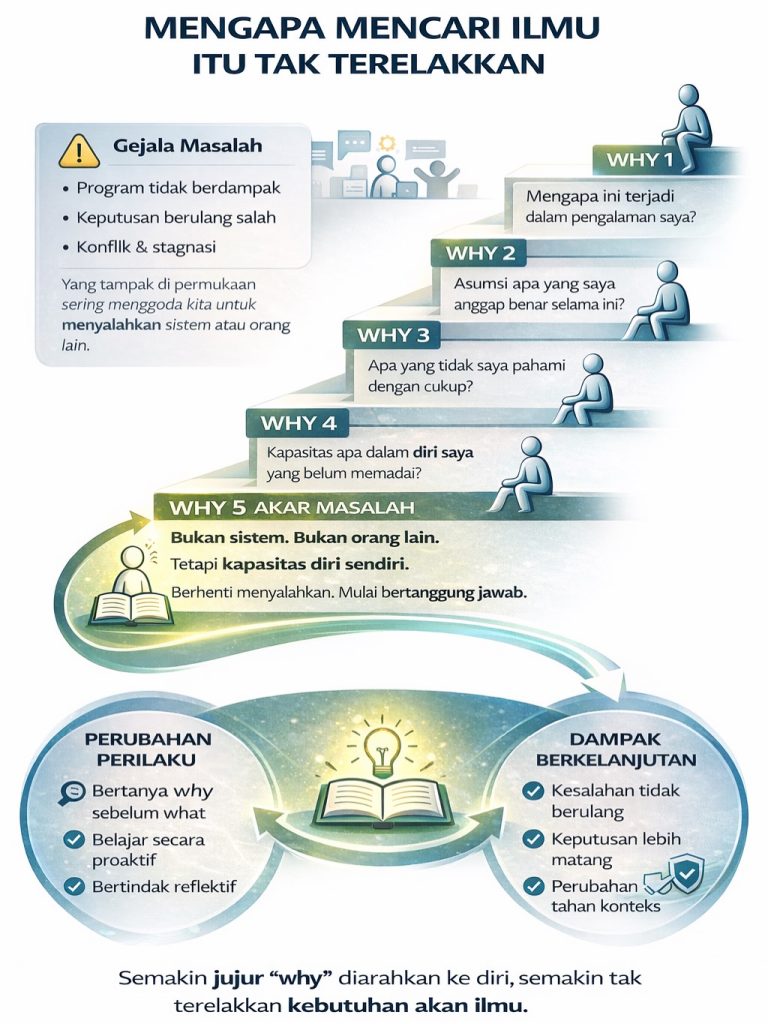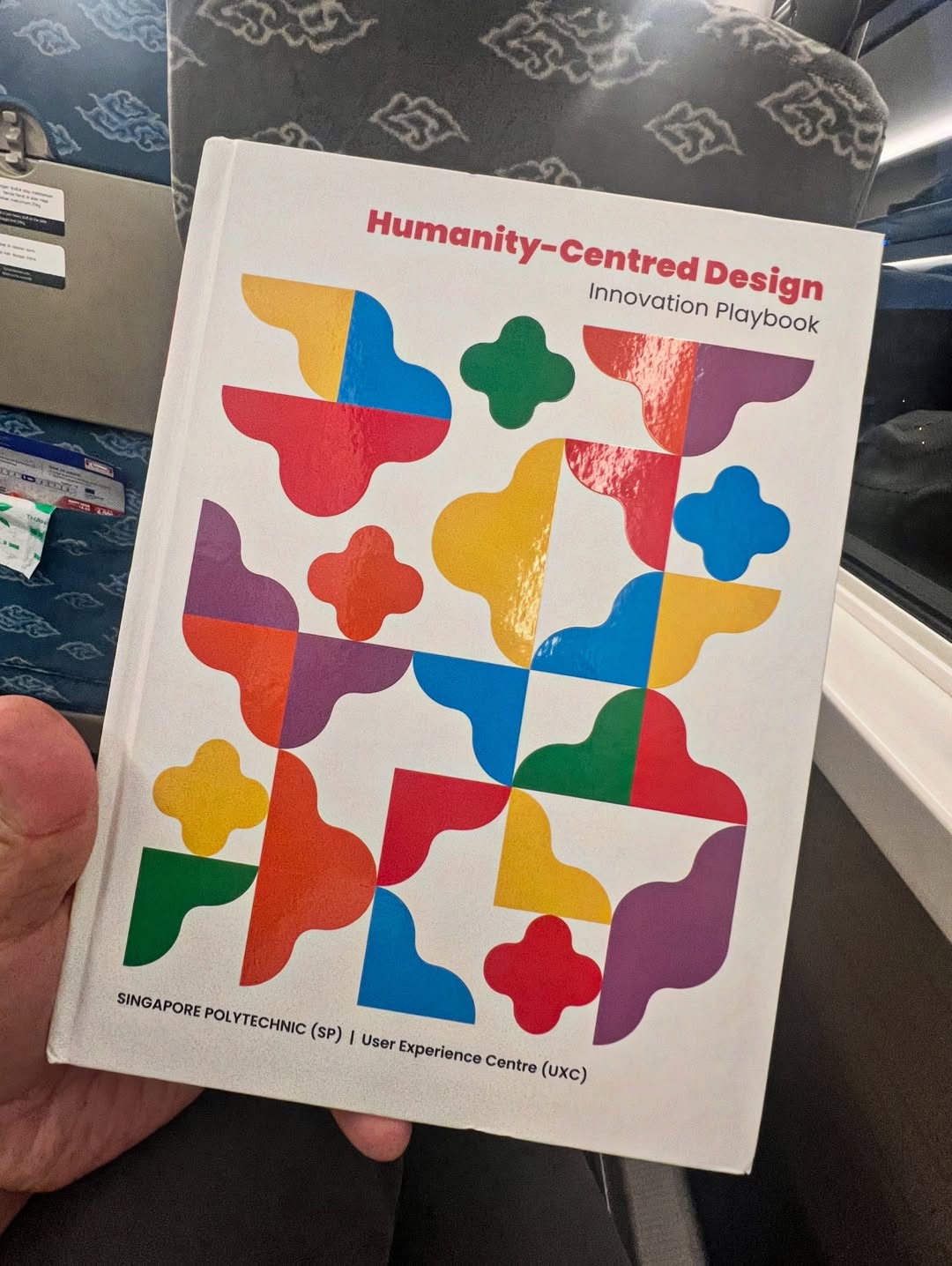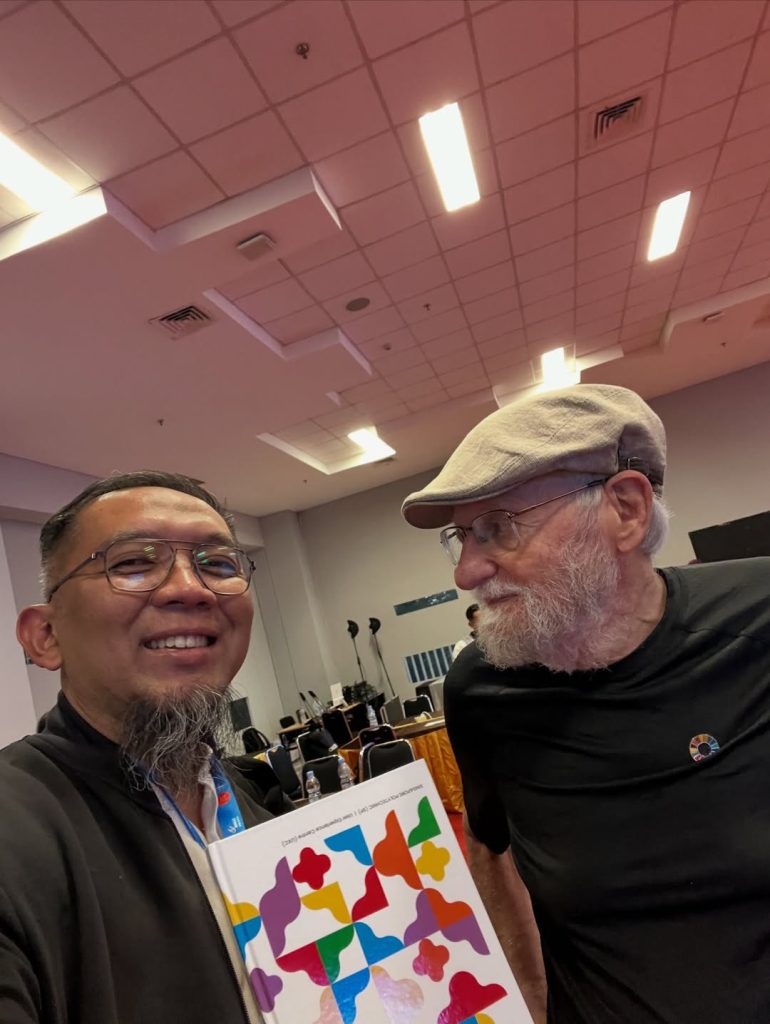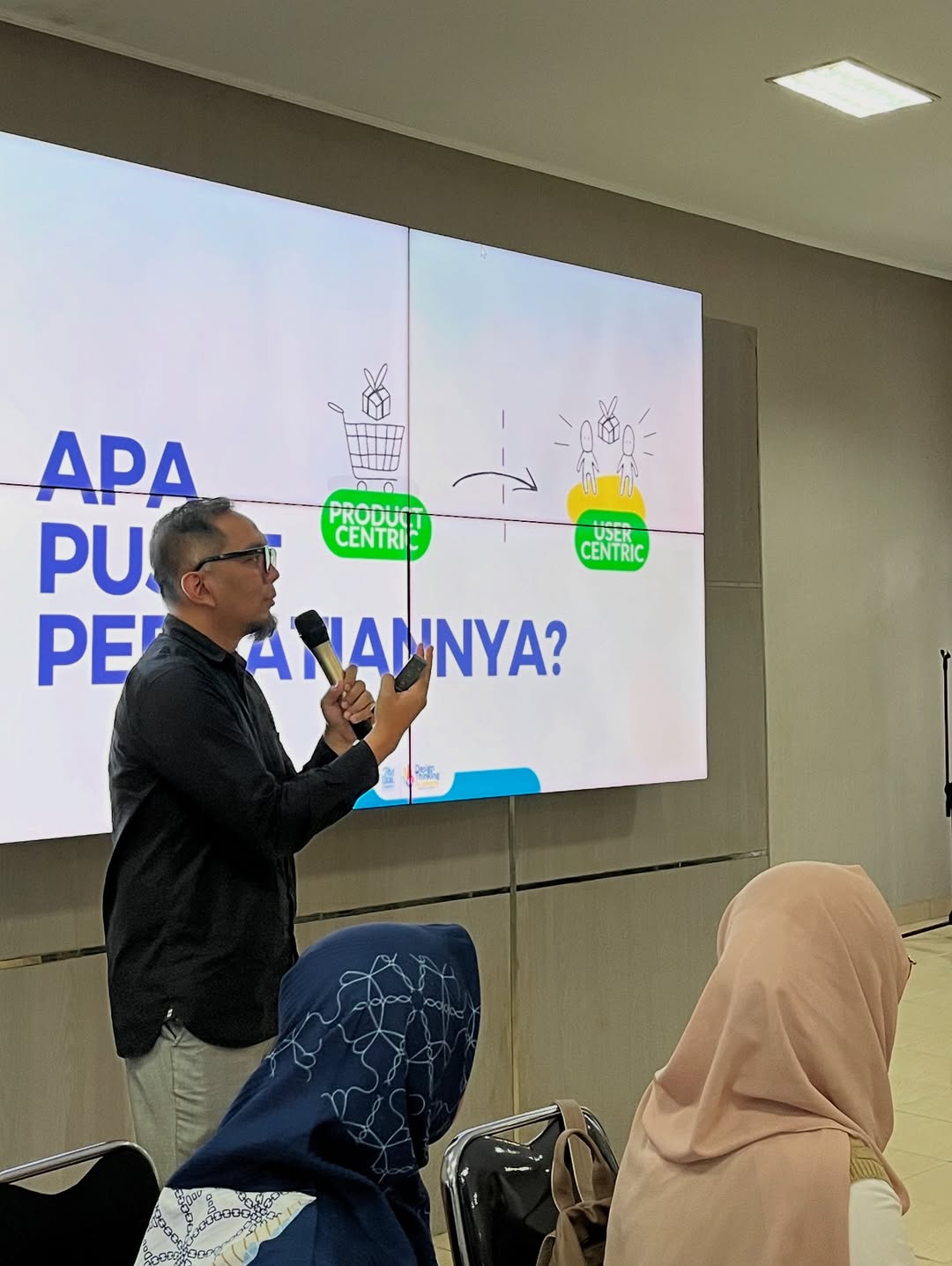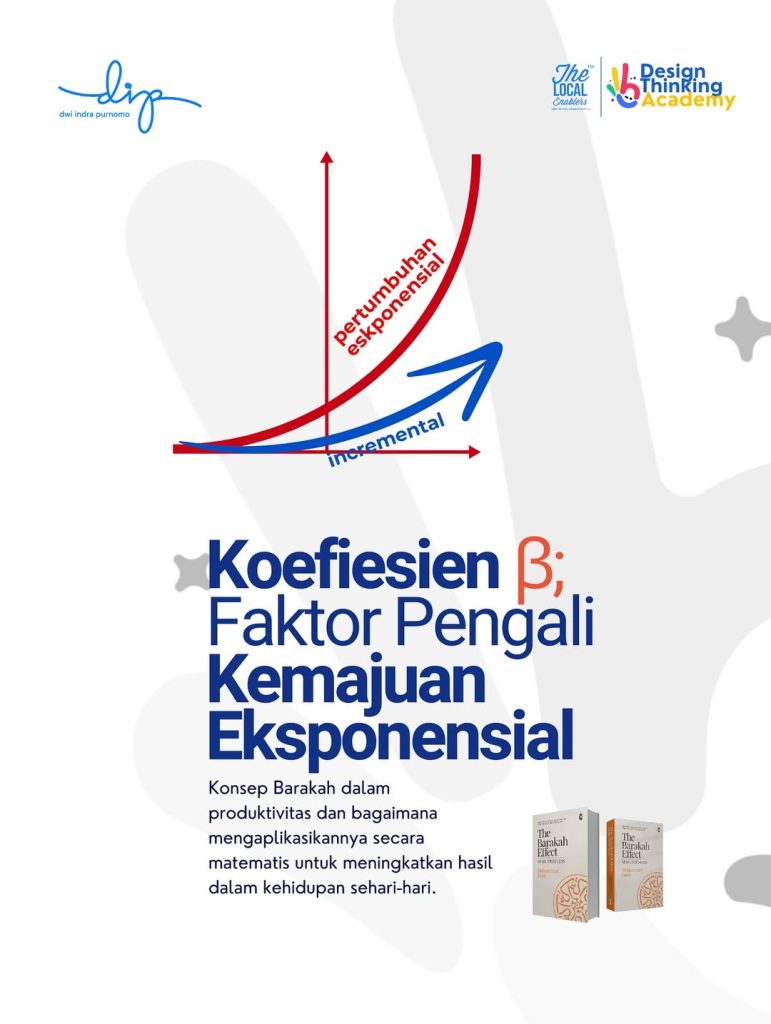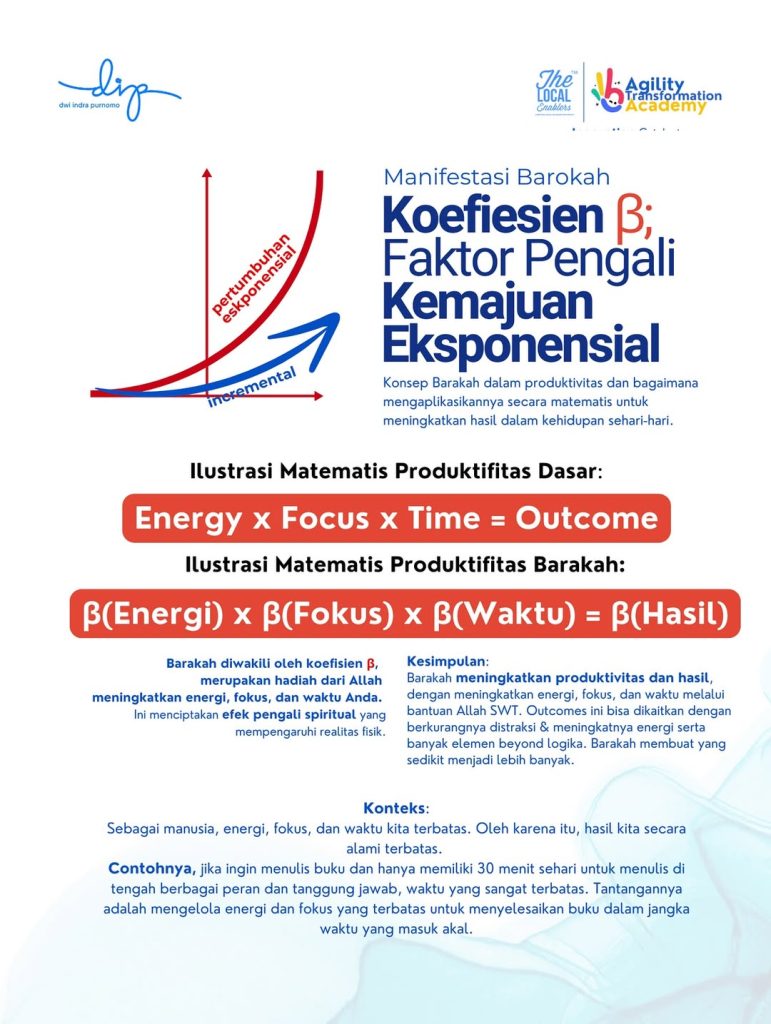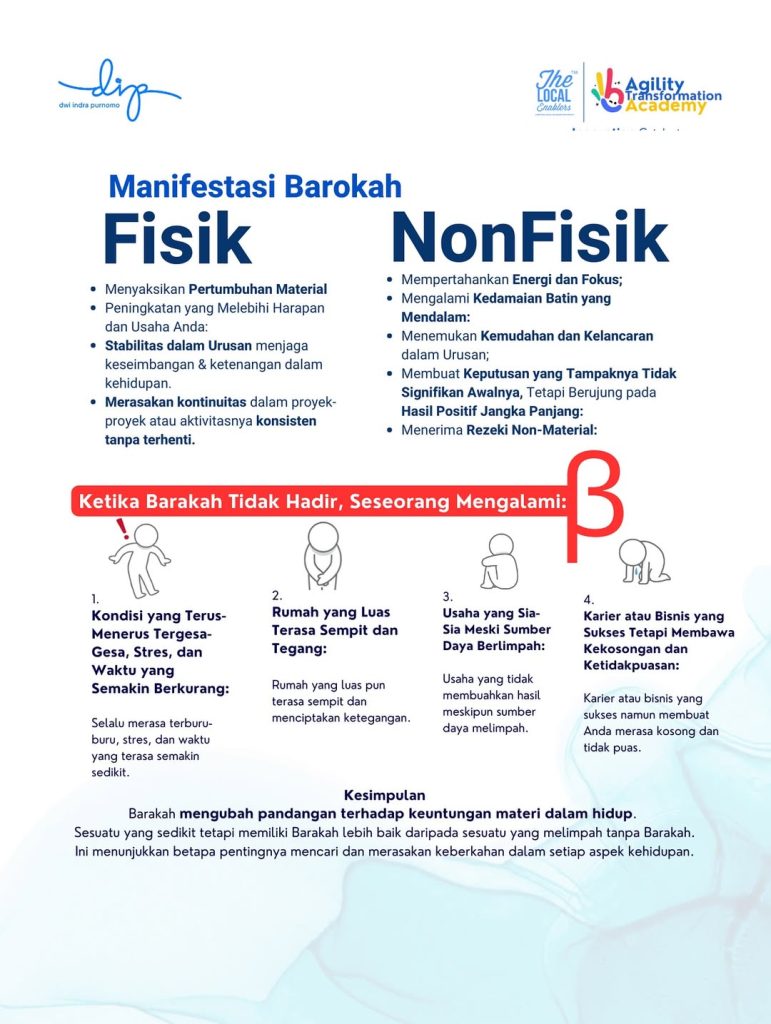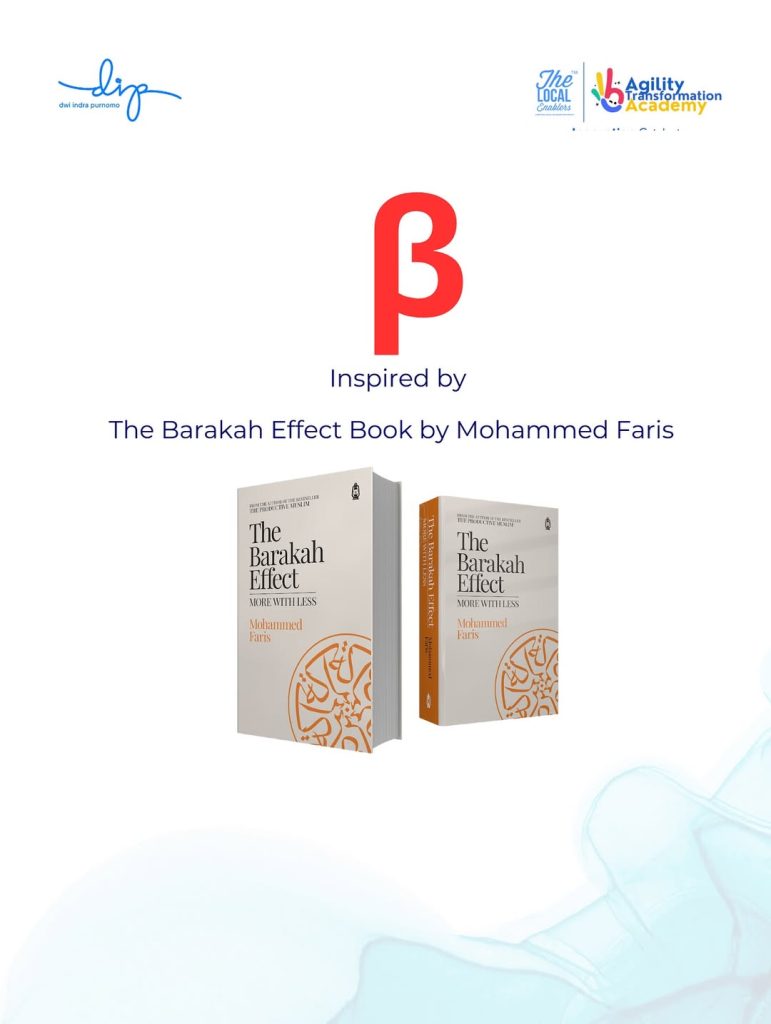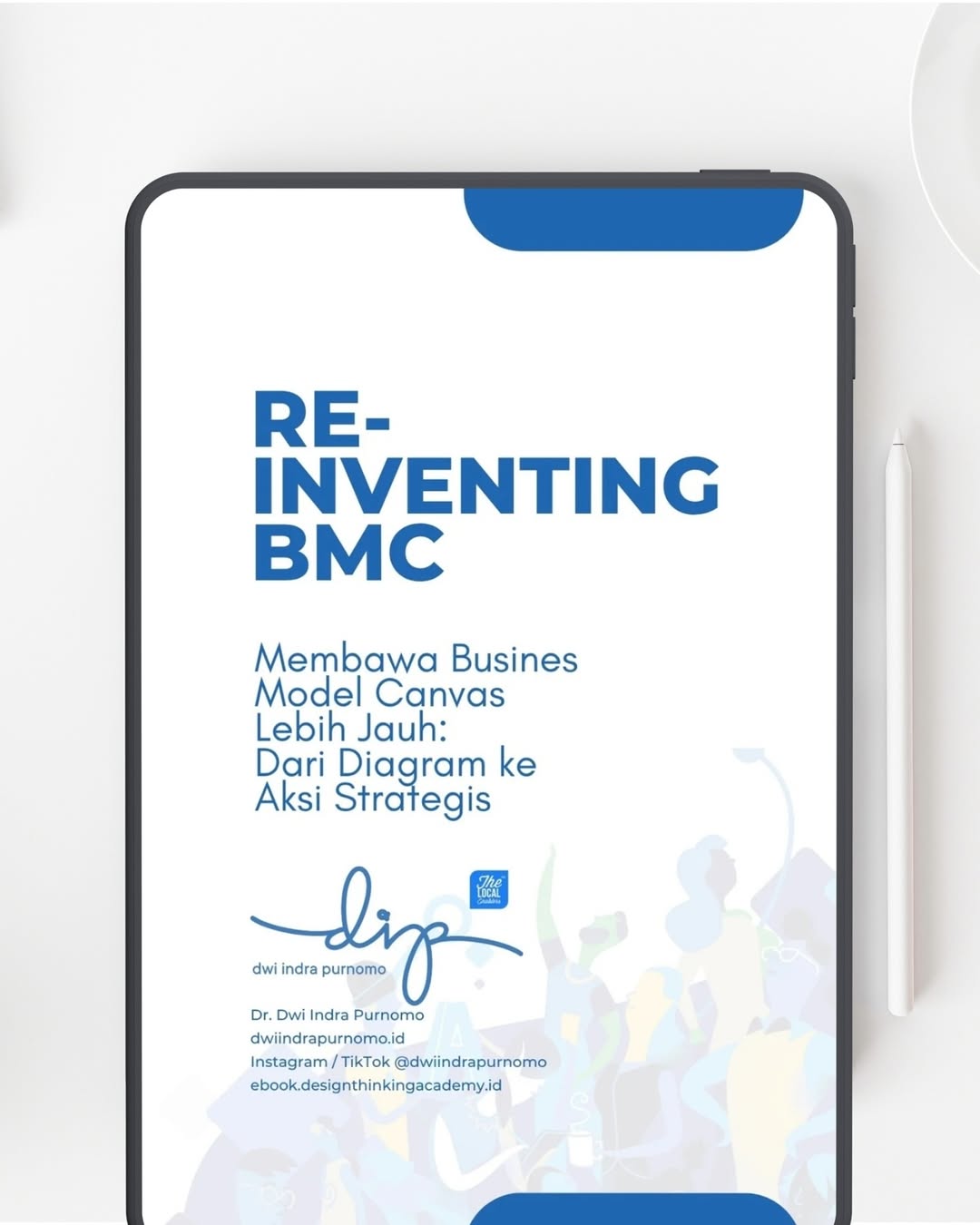Busyness Is Not Velocity:
Reframing Organizational Speed Through System Design Thinking.
Sering kali di dalam organisasi kita merasa sudah bekerja cepat. Aktivitas padat, rapat beruntun, dan eksekusi tanpa henti menciptakan ilusi kemajuan. Kita merasa berlari kencang. Padahal, yang sering terjadi hanyalah kelelahan yang bergerak, bukan perjalanan yang mendekat ke tujuan.
Di saat yang sama, ada organisasi lain yang melaju lebih cepat tanpa terlihat tergesa. Bukan karena orang-orangnya lebih kuat, tetapi karena mereka menggunakan kendaraan. Kendaraan itu bukan gedung atau struktur, melainkan sistem: cara mengambil keputusan, membagi peran, dan mengalirkan nilai. Dengan sistem yang tepat, energi tidak dihabiskan untuk bertahan, tetapi diubah menjadi arah dan kecepatan.
Berlari 🏃♂️🏃♂️selalu punya batas. Ketika berlari, kita tidak punya ruang untuk berpikir jernih atau berdiskusi substantif, yang ada hanya instruksi teknis dan respons sesaat. Untuk berdialog, kita harus berhenti. Sebaliknya, kendaraan 🚗🏎️🚌🚐memungkinkan kita melaju sambil berpikir, bergerak sambil menyelaraskan, dan berubah tanpa kehilangan arah.
Masalah utama banyak organisasi bukan kurangnya kerja keras, tetapi kegagalan membangun kendaraan 🚌. Kita sibuk melatih orang agar berlari lebih cepat, padahal yang menentukan sampai atau tidaknya sebuah perjalanan adalah sistem yang membawa mereka. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana dan menampar: apakah organisasi kita sedang melaju, atau hanya kelelahan bersama?
Busyness often feels like speed.
But what’s really moving is exhaustion.