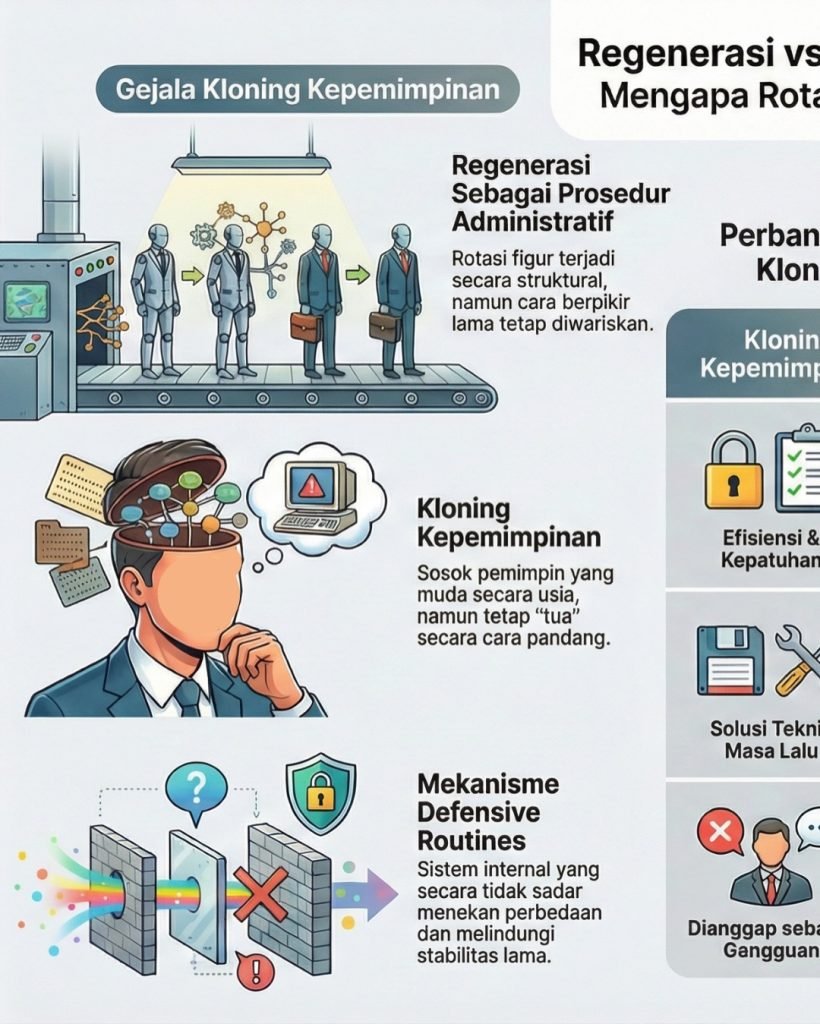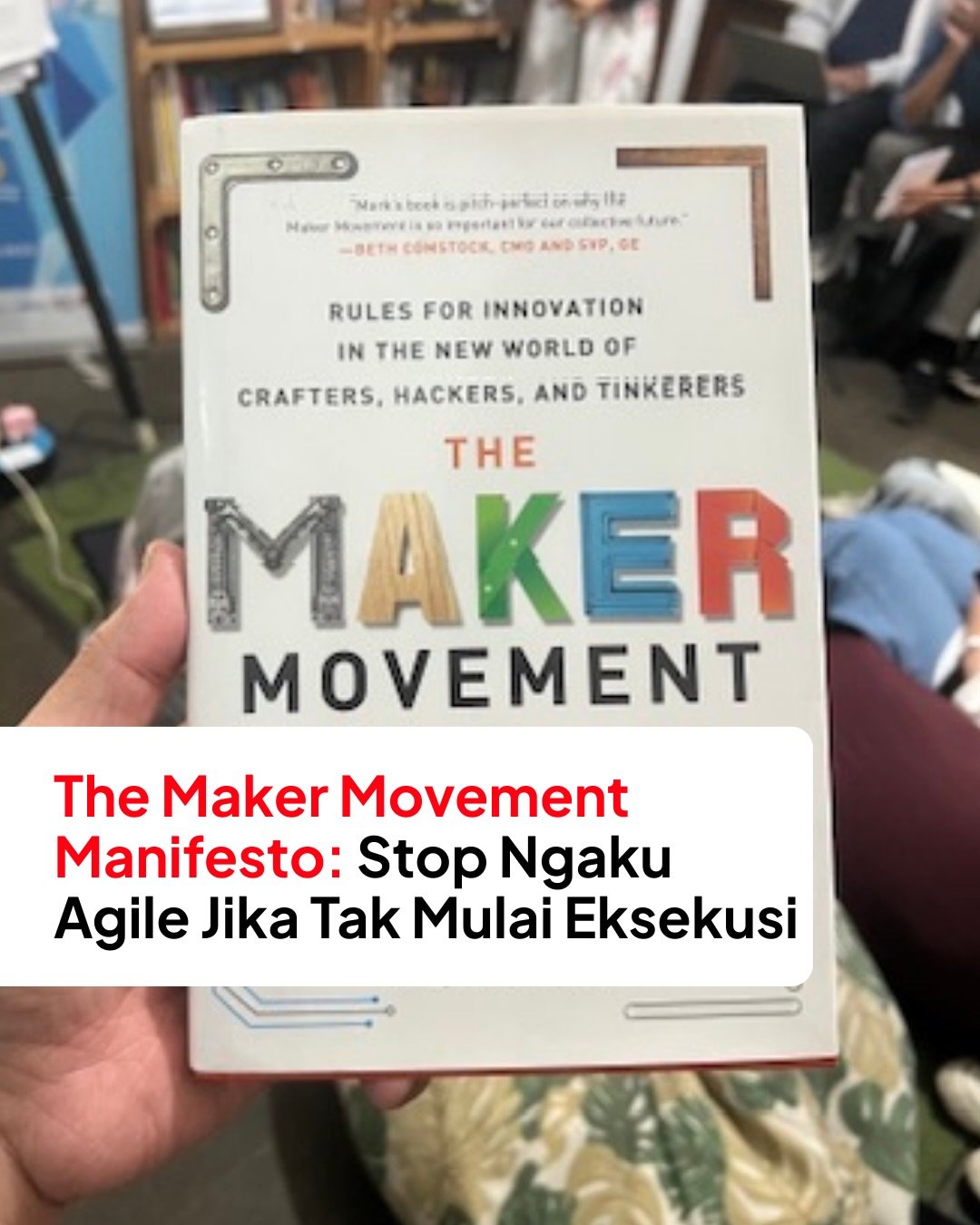Misi yang mudah diingat tidak lahir dari kalimat yang indah, tetapi dari keberanian memilih manusia dan perubahan apa yang benar-benar ingin diperjuangkan. Karena itu, misi sebaiknya dirumuskan dengan bahasa yang dekat dengan pengalaman hidup target yang dituju, bukan sekedar istilah institusional yang aman.

Kalimat seperti “membantu guru mengajar dengan lebih percaya diri” jauh lebih melekat daripada pernyataan umum tentang kualitas atau keunggulan. Misi semacam ini langsung memberi gambaran: jika manusia sasaran belum merasakan perubahan itu, maka misi belum benar-benar bekerja.

Misi yang membangkitkan semangat juga tidak berbicara tentang organisasi, melainkan tentang gap nyata yang dihadapi objek sasaran. Dengan merumuskan misi sebagai perjuangan, misalnya mendampingi pelaku usaha berani mengambil keputusan di tengah ketidakpastian, organisasi menetapkan standar yang jelas bagi dirinya sendiri. Setiap program dan kebijakan harus diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah ini benar-benar membantu manusia yang kita perjuangkan, atau sekadar membuat organisasi terlihat produktif?

Agar misi benar-benar hidup, ia harus konsisten muncul dalam cara organisasi bertindak, terutama saat menghadapi tekanan. Misi sejati diuji ketika target meleset, sumber daya terbatas, atau konflik muncul. Di saat seperti itulah misi seharusnya menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan. Jika dalam kondisi sulit misi selalu dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek dan kenyamanan sistem, maka misi tersebut pada dasarnya tidak pernah dimaksudkan untuk dijalankan.
Ketika misi dirumuskan dan dijalankan secara konsisten, visi tumbuh secara alami. Visi tidak lagi hadir sebagai janji besar yang membebani, tetapi sebagai gambaran masa depan yang masuk akal dan layak diperjuangkan. Orang-orang membangun visi bukan karena diminta, melainkan karena mereka merasakan bahwa misi yang mereka jalani hari ini nyata, bermakna, dan memberi harapan bagi masa depan bersama🙌🙌