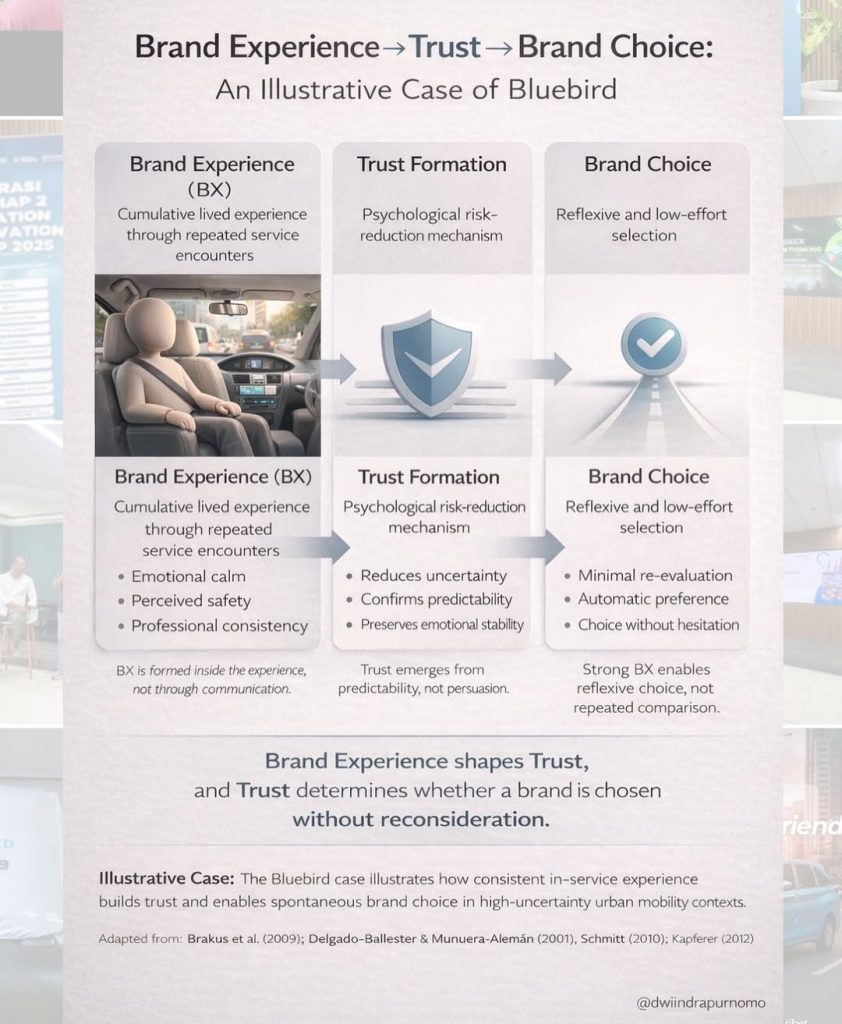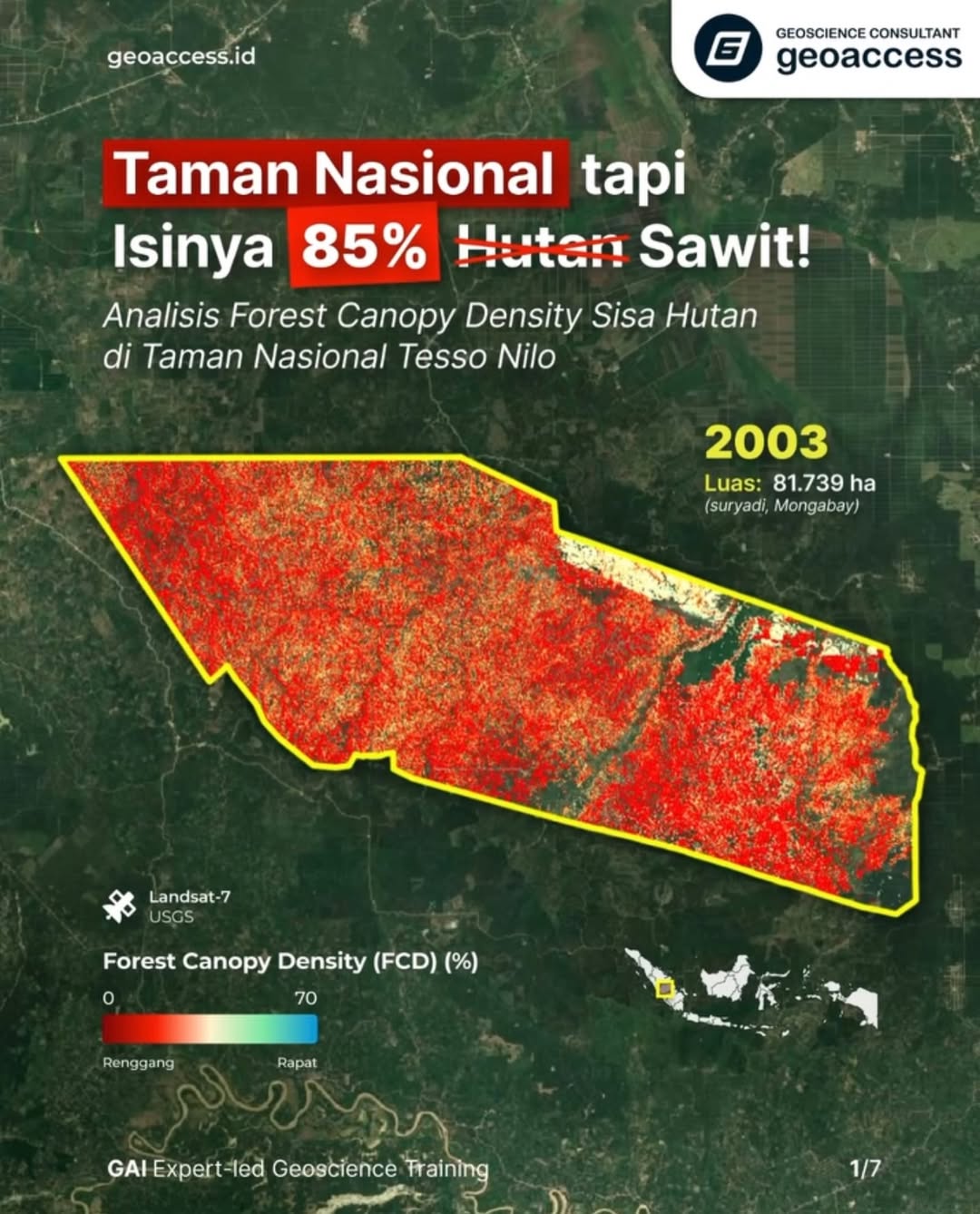Mengapa setiap kali inovasi dibicarakan di perusahaan, solusi yang muncul hampir selalu aplikasi atau AI? Ketika target tidak tercapai atau proses dianggap lambat, persoalan kerap dipersempit menjadi masalah teknis. Akibatnya, inovasi dipahami sebagai penambahan sistem, dashboard, atau otomatisasi. Padahal, di balik persoalan tersebut sering terdapat masalah yang lebih mendasar: alur kerja yang tidak jelas, peran yang tumpang tindih, serta tekanan pengambilan keputusan yang tinggi bagi karyawan.

Teknologi menjadi pilihan yang terlihat aman dan terukur. Aplikasi dapat diluncurkan, AI dapat dipresentasikan, dan kemajuan dapat dilaporkan dalam bentuk angka. Namun, di tingkat operasional, cara kerja sering kali tidak berubah. Proses lama hanya berpindah medium, sementara kompleksitasnya tetap. Formulir bertambah, persetujuan semakin berlapis, dan beban kerja karyawan justru meningkat. Dalam kondisi ini, teknologi tidak memperbaiki pengalaman kerja, melainkan menambah lapisan masalah baru.
Inovasi yang bermakna justru berangkat dari perbaikan cara kerja sebelum penerapan teknologi. Penyederhanaan proses, kejelasan peran dan tanggung jawab, serta pengambilan keputusan yang lebih rasional adalah fondasi utamanya. Ketika proses sudah logis dan manusiawi, teknologi akan berfungsi sebagai enabler, bukan beban. Dengan demikian, keberhasilan inovasi di perusahaan seharusnya diukur dari perubahan perilaku dan kualitas pengalaman kerja, bukan semata dari kecanggihan sistem yang digunakan.
Innovation fails not because technology is insufficient, but because the way people work is never fixed.