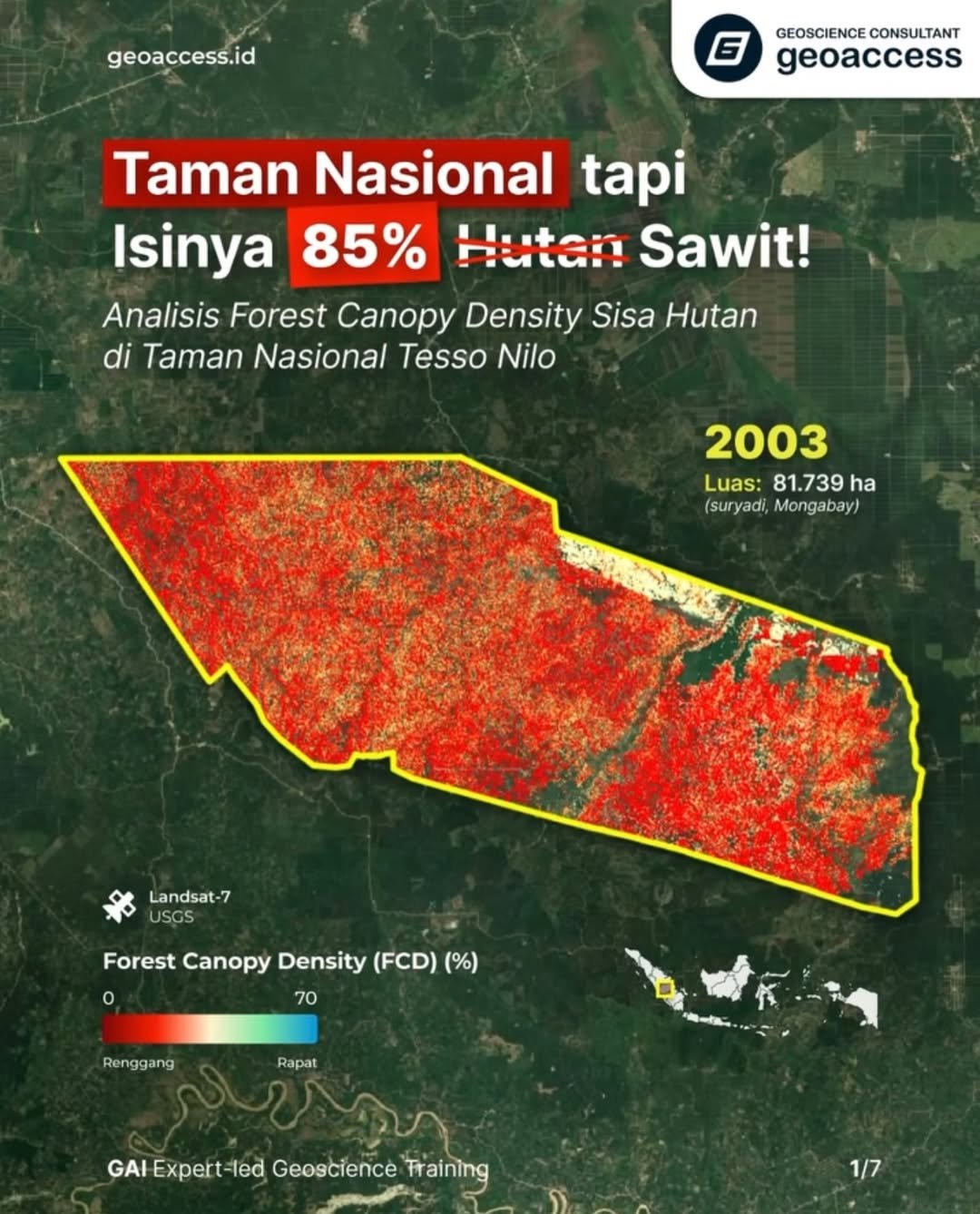Kasus yang menyeret nama Nadiem Makarim kerap dibingkai melalui narasi bahwa ia telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan pengemudi ojek daring. Dari sini muncul tuntutan moral agar para pengemudi “berterima kasih” atau bahkan membela. Masalahnya, logika “sudah memberikan pekerjaan” ini juga digunakan pemerintah. Ia bukan kasus tunggal, melainkan cerminan dari cara pandang negara yang keliru: ketika penciptaan pekerjaan dianggap telah memenuhi mandat kesejahteraan.

Fakta bahwa jutaan pengemudi ojek daring bekerja penuh waktu namun tetap hidup dalam kerentanan menunjukkan kegagalan kebijakan publik, bukan kegagalan individu atau pelaku usaha. Pendapatan yang fluktuatif, minim perlindungan sosial, risiko keselamatan tinggi, serta keterbatasan akses kesehatan dan pendidikan memperlihatkan bahwa negara membiarkan pekerjaan tumbuh tanpa sistem penyangga kesejahteraan. Dalam kondisi ini, beban kesejahteraan tidak dapat dialihkan kepada pengusaha yang menciptakan kerja, apalagi dijadikan sasaran atas masalah yang bersumber dari kegagalan sistemik.

Masalah utamanya terletak pada kegagalan pemerintah menjalankan fungsi negara secara utuh. Negara lemah sebagai regulator pelindung pekerja rentan, tidak efektif sebagai penyedia layanan publik dasar, dan tidak konsisten sebagai penjamin mobilitas sosial. Kebijakan ketenagakerjaan berjalan terpisah dari kebijakan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan jaminan sosial. Akibatnya, pekerjaan diperlakukan sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sebagai sarana menuju kesejahteraan.

Ketika keberhasilan pembangunan terus diukur terutama dari angka serapan tenaga kerja, negara sedang melakukan penyederhanaan kebijakan yang berbahaya. Tanggung jawab kesejahteraan dialihkan kepada individu dan pelaku usaha: selama pekerjaan tercipta, negara merasa tugasnya selesai. Kasus Nadiem seharusnya menjadi cermin untuk mengoreksi logika ini. Kritik yang relevan bukan pada siapa yang menciptakan pekerjaan, melainkan pada negara yang gagal memastikan bahwa bekerja benar-benar membawa warganya hidup lebih aman, lebih sehat, dan lebih bermartabat.